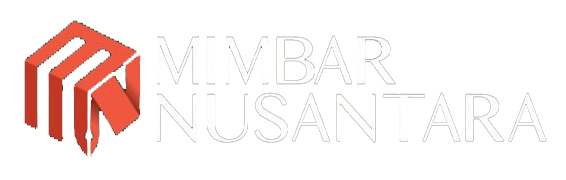PENUTUPAN Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbuka atau open dumping sebanyak 343 di sejumlah daerah telah terjadi pergeseran paradigma dalam tata kelola lingkungan.
Kebijakan penutupan ini, kata pakar lingkungan hidup Universitas Gadjah Mada Dr. Ir. Wiratni Budhijanto mencerminkan terjadinya pergeseran paradigma dalam tata kelola lingkungan.
Ia menegaskan perubahan paradigma ini menuntut kesiapan sistemik dari pemerintah daerah serta kesadaran kolektif masyarakat.
Dosen Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM ini menjelaskan secara prinsip saat ini yang terjadi di seluruh daerah terdapat dua jenis sistem pengelolaan akhir sampah, yaitu open dumping dan sanitary landfill.
Dalam sistem open dumping, katanya berarti sampah hanya ditumpuk begitu saja tanpa perlakuan lebih lanjut.
Sedangkan pada sanitary landfill, setiap lapisan sampah harus diurug dengan tanah agar proses pembusukan berjalan lebih baik dan dampak lingkungannya dapat ditekan.
“TPA di berbagai daerah semestinya mengadopsi sistem sanitary landfill. Namun, realitanya tidak selalu demikian. Karena sampah datang terus, pemerintah nggak bisa nunggu tanahnya ada atau bisa dibeli,” kata Wiratni, Selasa (22/4).
“Akhirnya TPA yang seharusnya sanitary landfill jadi open dumping juga. Padahal ini jelas tidak boleh,” jelasnya.
Selain memperburuk bau dan estetika, sistem terbuka ini juga menyebabkan proses pembusukan yang sangat lambat, menciptakan ‘gunung sampah’ yang tak kunjung hilang.
TPA Piyungan sendiri, lanjutnya, sudah sejak lama menunjukkan tanda-tanda kritis. Selain volume yang jauh melebihi kapasitas rancangannya, keberadaan permukiman yang semakin mendekat ke kawasan TPA menambah risiko sosial dan kesehatan.
Keputusan untuk menutup TPA tersebut tidak bisa dilepaskan dari urgensi multidimensi, mulai dari teknis, ekologis, hingga sosial.
“Sejak lima atau sepuluh tahun lalu sebetulnya TPA Piyungan itu sudah penuh. Dari aspek desain, lingkungan, dan sosial, memang sudah tidak layak lagi digunakan,” tegasnya.
Penutupan TPA terbuka mengedukasi warga
Wiratni menegaskan momen ini sebagai peluang besar untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah. Selama ini, keberadaan TPA justru memperkuat kebiasaan buruk membuang sampah tanpa pikir panjang.
“Kalau TPA ditutup, masyarakat jadi mikir. Buang sampah jadi susah, kita mulai introspeksi. Makan jangan sampai sisa, kemasan dikurangi, bawa tumbler sendiri. Ini mendidik,” ujarnya.
Di samping itu, kebijakan penutupan TPA open dumping juga diharapkan mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah, mengomposkan limbah organik di rumah, dan lebih sadar akan konsumsi sehari-hari.
Ia menyebutkan kebijakan ini juga menguji kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem desentralisasi pengelolaan sampah.
Setiap kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya sendiri. Wiratni menggambarkan kondisi ini seperti melepas bayi ke jalan raya.
Menurutnya desentralisasi yang ideal seharusnya dilakukan secara bertahap, disertai dukungan teknis dan pendampingan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Sebagai bagian dari upaya masif edukasi publik, saat ini UGM bersama sejumlah perguruan tinggi lain di Indonesia merancang program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertema edukasi persampahan secara serentak.
Para mahasiswa akan turun langsung ke masyarakat untuk melakukan edukasi dari rumah ke rumah, dengan pendekatan persuasif.
“Semua kampus akan turunkan mahasiswa KKN untuk melakukan edukasi ke rumah-rumah. Ini supaya masyarakat bisa lebih sadar, seberapa besar sampah yang mereka hasilkan dan bagaimana mereka bisa mengurangi,” tuturnya.
Wiratni mengajak warga masyarakat dan pemda agar menjadikan momentum penutupan TPA open dumping ini sebagai titik balik perbaikan sistem dan budaya. (AGT/S-01)